Menurut Peter Carey dalam tulisan “Percakapan dengan Diponegoro (2022)”, hari kelahirannya dianggap sangat beruntung dalam penanggalan Jawa karena bertepatan dengan bulan Sura, yang merupakan bulan pertama tahun Jawa menandai awal dari pendirian kerajaan serta awal dari gelombang sejarah baru.
ZONA PERANG(zonaperang.com) – Pangeran Diponegoro (ꦢꦶꦥꦤꦼꦒꦫ) (lahir Bendara Raden Mas Mustahar ; kemudian Bendara Raden Mas Antawirya ) (11 November 1785 – 8 Januari 1855), juga dikenal sebagai Dipanegara, adalah seorang pangeran Jawa yang menentang pemerintahan kolonial Belanda.
Lahir dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III Yogyakarta.
“Pangeran Diponegoro lahir di Kaputren, Keraton Yogyakarta saat fajar menjelang ketika sahur pada 8 Muharam 1200 H atau tanggal 11 November 1785 antara pukul 3.30-4.00. Kelahirannya pada Jumat Wage memiliki makna penting dalam catatan almanak atau primbon Jawa yang digunakan secara modern.”
Beliau adalah putra tertua Sultan dan memainkan peran penting dalam Perang Jawa antara 1825 dan 1830(Perang yang sangat merugikan Belanda). Setelah kekalahan dan penangkapannya, ia diasingkan ke Makassar, di mana ia meninggal, 69 tahun.
Perjuangannya selama lima tahun melawan kontrol Belanda atas Jawa dikenang rakyat Indonesia, bertindak sebagai sumber inspirasi bagi para pejuang dalam Revolusi Nasional Indonesia dan nasionalisme di Indonesia modern.Dia adalah pahlawan nasional di Indonesia.
https://www.youtube.com/watch?v=-WYF6tE4Jlw
Baca juga : Robert Wolter Mongisidi (Manado, February 14, 1925 – Makassar, September 5, 1949)
Pangeran Diponegoro Menolak Diangkat Menjadi Raja
Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri.
Perang Diponegoro
Sekitar 1825-1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir-hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia.
Pemerintahan kolonial Belanda menjadi tidak populer di kalangan petani lokal karena kenaikan pajak, gagal panen dan di kalangan bangsawan Jawa karena penguasa kolonial Belanda merampas hak mereka.
Letusan Gunung Merapi pada tahun 1822 dan wabah kolera pada tahun 1824 memperkuat dukungan luas untuk Diponegoro.
Pada hari-hari menjelang pecahnya perang, tidak ada tindakan yang diambil oleh pejabat lokal Belanda meskipun desas-desus tentang pemberontakannya yang akan datang telah beredar.
Di Awal perang kerugian besar menghampiri pihak Belanda, karena kurangnya strategi dan komitmen yang dalam memerangi perang gerilya Diponegoro.
Belanda akhirnya berkomitmen untuk mengendalikan pemberontakan yang meluas dengan menambah jumlah pasukan dan mengirim Jenderal De Kock untuk menghentikan pemberontakan. De Kock mengembangkan strategi kamp yang dibentengi (benteng) dan pasukan bergerak.
Barak tentara yang dijaga ketat menduduki tempat-tempat penting untuk membatasi pergerakan pasukan Diponegoro sementara pasukan bergerak berusaha mencari dan melawan pemberontak.
Sejak tahun 1829, Diponegoro secara definitif kehilangan inisiatif pertempuran dan ditempatkan pada posisi bertahan oleh Belanda. melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya.
Penjajah Belanda membuat taktik sayembara barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar yaitu 20.000 gulden. Akan tetapi, pengikut Pangeran Diponegoro pada saat itu tidak goyah akan tawaran tersebut.
Akhir Perlawan

Diponegoro menuntut negara merdeka di bawah seorang sultan dan ingin menjadi pemimpin Islam (khalifah) di seluruh Jawa. Pada bulan Maret 1830 ia diundang untuk berunding di bawah bendera gencatan senjata.
Beliau diterima dan bertemu di kota Magelang tetapi ditawan pada 28 Maret meskipun ada bendera gencatan senjata.
Situasi penangkapan Diponegoro dilihat berbeda oleh dirinya dan Belanda. Yang pertama melihat penangkapan itu sebagai pengkhianatan karena bendera gencatan senjata, sementara yang kedua menyatakan bahwa dia telah menyerah.
Penggambaran peristiwa tersebut, oleh Raden Saleh dari Jawa dan Nicolaas Pieneman dari Belanda, menggambarkan Diponegoro secara berbeda – yang pertama memvisualisasikannya sebagai korban yang menantang, yang terakhir sebagai pria yang ditundukkan.
Segera setelah penangkapannya, Beliau dibawa ke Semarang dan kemudian ke Penjara Batavia(Museum Sejarah Jakarta) di ruang Ex-Kepala Sipir karena statusnya sebagai seorang Pangeran .
Pada tahun 1830, ia dibawa ke Manado, Sulawesi selama beberapa tahun lalu kembali dipindahkan ke Makassar pada Juli 1833 di mana ia ditahan di Fort Rotterdam karena Belanda percaya bahwa penjara tidak cukup kuat untuk menampungnya.
Terlepas dari status tahanannya, istrinya Ratnaningsih dan beberapa pengikutnya menemaninya ke pengasingan dan dia menerima pengunjung terkenal termasuk Pangeran Henry Belanda yang berusia 16 tahun pada tahun 1837.
Diponegoro juga menyusun manuskrip tentang sejarah Jawa dan menulis otobiografinya, Babad Diponegoro, selama pengasingannya. Kesehatan fisiknya memburuk karena usia tua. Beliau meninggal pada 8 Januari 1855saat berumur 69 tahun.
Sebelum meninggal, Diponegoro mengamanatkan agar dimakamkan di Kampung Melayu, lingkungan yang saat itu dihuni oleh orang Tionghoa dan Belanda. Ini diikuti, dengan Belanda menyumbangkan 1,5 hektar (3¾ acre) tanah untuk kuburannya yang saat ini telah menyusut menjadi hanya 550 meter persegi (6000 sq. ft.). Kemudian, istri dan pengikutnya juga dimakamkan di kompleks yang sama.
Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri dari 9 wanita yang dinikahinya.
Penghargaan
*KRI Diponegoro (365), Diponegoro-class corvette
*Universitas Diponegoro (Undip)
https://www.youtube.com/watch?v=aqmQbNLR2Do










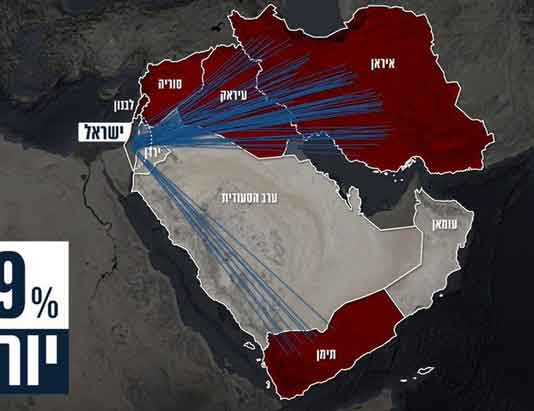


![Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary; 21 April 1926 – 8 September 2022) adalah Ratu Britania Raya[a] dari 6 Februari 1952 hingga kematiannya pada 2022. Pemerintahannya selama 70 tahun dan 214 hari adalah yang terlama dari semua raja Inggris dan catatan terpanjang kedua dari raja mana pun di negara berdaulat. Pada saat kematiannya, Elizabeth juga adalah Ratu dari 14 kerajaan Persemakmuran lainnya, selain Inggris.](https://zonaperang.com/wp-content/uploads/2022/09/HM_The_Queen_Small_Portrait.jpg)

