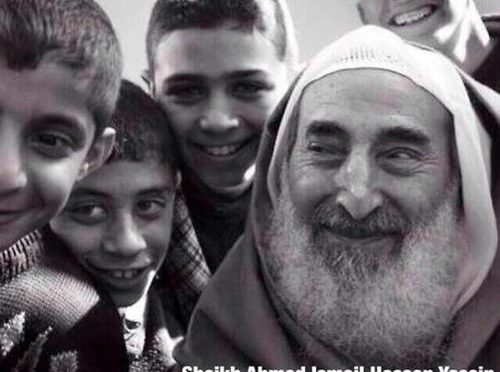Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan politik dan sosial yang memuncak di masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang dianggap represif terhadap kebebasan beragama dan hak-hak sipil. Tanjung Priok, sebuah kawasan pelabuhan yang padat di Jakarta Utara, menjadi saksi tragedi yang merenggut nyawa puluhan hingga ratusan orang akibat bentrokan antara warga dan aparat keamanan.
ZONA PERANG (zonaperang.com) – Tanggal 12 September 1984, adalah titi mangsa yang begitu kelabu bagi umat muslim. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tertumpah. Dari percik pemantik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada 12 September 1984.
Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah kala itu. Korban tewas nyaris seluruhnya meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an.
“Tanjung Priok, sebuah kawasan pelabuhan di Jakarta Utara, menjadi pusat aktivitas politik dan sosial. Kawasan ini didominasi oleh masyarakat Muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Pada saat itu, terdapat ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Tanjung Priok, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan dan hak-hak sipil.”
Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila dan NKRI (Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi, 2015: 161).
Baca juga : Perjanjian Hudaibiyah: Kontroversi dan Keuntungan Strategis bagi Umat Islam
Baca Juga : Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, Pemimpin DI/TII yang dihukum mati sahabat karibnya
Mereka yang Dituding Subversif
subversi yang berarti gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang(kbbi.web.id/) di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibukota.
Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional.
Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Djaelani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi “resmi” pemerintah.
Selepas subuh usai peristiwa Tanjung Priok, Djaelani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu.
Djaelani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya (Tempo, Volume 23, 1993:14). Selain Djaelani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy, Hasan Kiat, dan lainnya, yang dituding sebagai “aktor intelektual” bentrokan tersebut.
Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi, hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Djaelani.
Djaelani sempat menyampaikan eksepsi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984 itu. Kesaksian Djaelani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan judul eksepsi pembelaannya di pengadilan (A.Q. Djaelani, Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap Umat Islam Indonesia: Sebuah Pembelaan, 1985).
Pemantik Bentrok di Tanjung Priok
Dalam eksepsi pembelaannya, Djaelani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Sabtu, 8 September 1984, dua Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil datang ke Musala As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok.
Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Djaelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut.
Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah seorang anggota Babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi, dengan dalih: ”… pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilox yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya.
Maka, tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan.” (Irfan S. Awwas, ed., Bencana Umat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000, 2000:30). Kelakuan dua Babinsa ini segera menjadi kasak-kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespons secara frontal.
Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar.
Dua hari kemudian, masih dari penuturan Djaelani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musala dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musala.
Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator.
Empat orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, kata Djaelani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar.
Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil.
Baca Juga : Sejarah Panjang Penganiayaan Minoritas Muslim di Myanmar(Burma)
Baca Juga : Tragedi Keluarga Shalahuddin Menjual Baitul Maqdis kepada Frederick II (Perang Salib Keenam)
Massa vs Aparat
Amir Biki segera merespons permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu (Kontras, Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok, 2004:19).
Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang, undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya.
Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah. Namun, oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut.
Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru: “Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko.
Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya!” “Kita tidak boleh merusak apapun! Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita,” lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah, seperti dituturkan Abdul Qadir Djaelani dalam persidangan.
Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka paginya, 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekira 200 meter.
Kontroversi Jumlah Korban
Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan, tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser (Kontras, 2004: 20).
Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru.
Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi-buta. Bahkan, seorang saksi mata mendengar umpatan dari salah seorang tentara yang kehabisan amunisi. “Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak!” (Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa?, 1998: 32).
Dari arah pelabuhan, dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk.
Pernyataan Djaelani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa.
Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki (Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, 2001: 56). Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang, dalam tragedi di Tanjung Priok karena pemerintah saat itu menutupi fakta yang sebenarnya.
Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut (A.M. Fatwa, Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, 2005: 123).
Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) yang juga didukung oleh kesaksian Djaelani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang (Suara Hidayatullah, Volume 11, 1998: 67).
Pemerintahan saat itu hingga saat ini tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu hingga tuntas.
Setelah Tragedi: Penindasan dan Pengabaian Keadilan
Setelah insiden tersebut, pemerintah Orde Baru mencoba meredam dampak dari tragedi dengan menutup informasi dan melakukan kontrol ketat terhadap media. Pemerintah menahan sejumlah tokoh dan aktivis yang dianggap terlibat dalam aksi tersebut, sementara korban luka dan keluarga korban tewas merasa diabaikan. Pada saat yang sama, tidak ada penyelidikan menyeluruh yang dilakukan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan.
Pemerintah berusaha menampilkan peristiwa ini sebagai insiden yang disebabkan oleh “oknum” radikal, tetapi di mata banyak orang, tragedi Tanjung Priok menjadi simbol dari otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia di era Orde Baru. Peristiwa ini semakin mempertegas pandangan bahwa rezim Soeharto tidak segan-segan menggunakan kekuatan brutal untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan setiap bentuk perlawanan.
Dampak dan Warisan
Tragedi Tanjung Priok meninggalkan luka mendalam di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yang merasa kebebasan mereka dibatasi oleh rezim yang otoriter. Peristiwa ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto, yang pada akhirnya tumbang pada 1998.
Setelah reformasi, tuntutan untuk mengusut tuntas peristiwa Tanjung Priok semakin kuat. Pada tahun 2000-an, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan dan menetapkan bahwa tragedi tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Beberapa perwira militer yang terlibat dalam insiden ini diadili di pengadilan HAM, meskipun banyak pihak yang merasa bahwa proses hukumnya tidak memadai dan keadilan belum sepenuhnya ditegakkan bagi para korban dan keluarga mereka.
Baca Juga : 21 Agustus 1969: Mesjid Al Aqsha Dibakar oleh Ekstrimis Yahudi