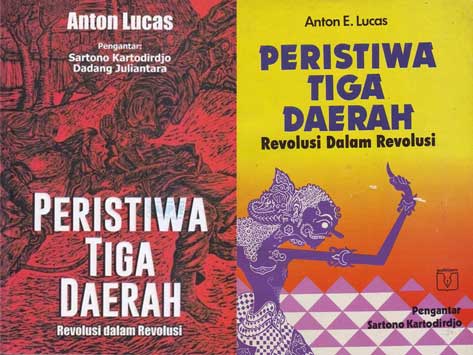ZONA PERANG(zonaperang.com) Resimen Marechaussee Tentara Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Jenderal G.C.E. van Daalen/Gotfried Coenraad Ernst van Daalen melancarkan kampanye militer untuk merebut Dataran Tinggi Gayo, Dataran Tinggi Alas, dan Dataran Tinggi Batak di wilayah Sumatera Utara, yang berakhir dengan pembantaian massal terhadap orang-orang Aceh dan Batak.
“Korps Marechaussee te Voet, di Indonesia dikenal sebagai Marsose, adalah satuan militer yang dibentuk pada masa kolonial Kerajaan Belanda oleh KNIL /Koninklijk Nederlands Indisch Leger (tentara kolonial) sebagai tanggapan taktis terhadap perlawanan gerilya di Aceh.”
Pada masa Sultan Iskandar Muda Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi juga daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri.
Baca juga : Ketika Amerika Menginvasi Aceh pada 1832
Baca juga : 16 Juni 1948, Dakota RI-001 Seulawah : Dari Aceh untuk Republik Indonesia dan perampokan didalamnya
Perang Aceh
Perang Atjeh (Perang Aceh), juga dikenal sebagai Perang Belanda atau Perang Kafir (1873-1904), adalah konflik militer bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda yang dipicu oleh diskusi antara perwakilan Aceh dan Amerika Serikat di Singapura pada awal tahun 1873. Perang ini merupakan bagian dari serangkaian konflik pada akhir abad ke-19 yang mengukuhkan kekuasaan Belanda atas Indonesia modern.
Protektorat Kesultanan Utsmaniyah
Kemerdekaan Aceh telah dijamin oleh Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 dan statusnya sebagai protektorat Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-16. Selama tahun 1820-an, Aceh menjadi kekuatan politik dan perdagangan regional, memasok setengah dari lada dunia, yang meningkatkan pendapatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan setempat.
Kesultanan Aceh membawa kerajaan-kerajaan daerah di bawah kendalinya dan memperluas wilayah kekuasaannya di pantai timur. Namun, kecenderungan ke selatan ini berbenturan dengan ekspansi kolonialisme Belanda ke arah utara di Sumatra.
Pembukaan Terusan Suez dan akhir klaim teritorial Inggris di Sumatra
Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perubahan rute pelayaran, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1871 yang mengakhiri klaim teritorial Inggris di Sumatra, yang memungkinkan Belanda memiliki kebebasan dalam lingkup pengaruhnya di Asia Tenggara Maritim sambil memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengawasi pembajakan.
Sebagai imbalannya, Inggris mendapatkan kendali atas Gold Coast Belanda di Afrika(bagian dari pesisir Teluk Guinea) dan hak-hak komersial yang setara di Siak Riau. Ambisi teritorial Belanda di Aceh didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, terutama lada hitam dan minyak, dan untuk menyingkirkan pemain pribumi yang merdeka. Belanda juga berusaha untuk menangkal kekuatan kolonial saingannya yang memiliki ambisi di Asia Tenggara, terutama Inggris dan Prancis.
“SultanAceh juga berusaha membentuk aliansi dengan Prancis dengan mengirim surat kepada Raja Prancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Prancis ke II (1849).”
Baca juga : Gerakan Aceh Merdeka(GAM) / Free Aceh Movement – Latar belakang, Tokoh, Perkembangan dan Penyelesaiannya
Baca juga : Pembantaian Etnis Melayu 1946: Kekejaman PKI (Partai Komunis Indonesia) di Sumatera Timur
Menuai kontroversi di Belanda
“Sultan Alauddin Muhammad Da’ud Syah II (1864 – 6 Februari 1939) adalah sultan Aceh yang ke tiga puluh lima dan terakhir di Sumatera Utara. Ia memerintah dari tahun 1875 hingga 1903 dalam perlawanannya terhadap kolonial Belanda.”
Kampanye ini menuai kontroversi di Belanda karena foto-foto dan laporan tentang jumlah korban tewas dilaporkan. Pemberontakan berdarah yang terisolasi terus berlanjut hingga tahun 1914 dan bentuk-bentuk perlawanan Aceh yang tidak terlalu keras terus berlanjut hingga Perang Dunia II dan pendudukan Jepang.
Baca juga : Peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh(Zeven Provinciën), Perlawanan Kelasi Bumiputra di kapal Belanda
Baca juga : 19 Mei 2003, Operasi militer Indonesia di Aceh dimulai