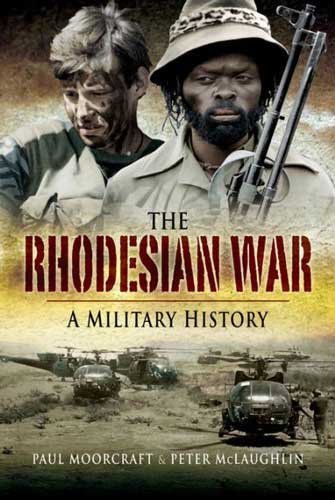Pembantai 6.000 Ulama dan Keluarga
ZONA PERANG(zonaperang.com) – Amangkurat I adalah raja Kesultanan Mataram keempat yang memerintah antara 1646-1677. Selama berkuasa, ia dikenal sebagai raja yang zalim. Perilakunya tersebut disebabkan oleh banyaknya percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan yang mewarnai pemerintahannya. Periode kekuasaan Amangkurat I juga menandai kemunduran Kerajaan Mataram Islam yang sempat mencapai puncak kejayaan ketika diperintah ayahnya, Sultan Agung (1613-1645).
Amangkurat I lahir pada 1618 atau 1619 dengan nama Raden Mas Sayyidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dari istrinya yang bergelar Ratu Wetan, putri Adipati Batang. Menurut silsilahnya, ia adalah cicit dari Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat I memiliki dua permaisuri yang bergelar Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Dari Ratu Kulon inilah ia mendapatkan putra mahkota bernama Pangeran Adipati Anom, yang kemudian mewarisi takhta Mataram dan memerintah dengan gelar Amangkurat II. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratu Wetan, Amangkurat I memiliki keturunan bernama Pangeran Puger, yang kemudian bergelar Pakubuwono I.
Baca Juga : Sultan Agung Hanyokrokusumo : Penguasa Pertama yang berani melawan VOC
Kekejaman Amangkurat I
Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik takhta dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya.
Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Menurut Babad ing Sengkala, pada 1647 Amangkurat I memindahkan keraton dari Kotagede ke Plered. Sejak awal pemerintahannya, ia tidak segan membunuh para pejabat yang dianggap tidak patuh dan kurang menghormatinya.
Beberapa bangsawan yang menjadi korbannya adalah Tumenggung Wiraguna, Pangeran Alit, dan Pangeran Pekik, ayah mertuanya. Jauh sebelum berkuasa, Amangkurat I memang pernah terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna dibunuh ketika menjalankan perintahnya untuk menyerang Kerajaan Blambangan.
Kesal dengan sikap kakaknya, Pangeran Alit memberontak dengan berbekal dukungan dari para ulama. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Alit. Setelah itu, Amangkurat I membantai ulama dan siapa saja yang dianggap merongrong kekuasannya.
Menurut laporan Rijcklof van Goens, Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 1678-1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Pada 1659, Amangkurat I memerintahkan untuk membunuh Pangeran Pekik, ayah mertuanya, beserta keluarganya.
Alasannya adalah Pangeran Pekik berani menikahkan gadis yang hendak dijadikan selirnya dengan putranya. Ditambah lagi, terdapat kebijakan Amangkurat I menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal di wilayah pesisir. Wilayah tersebut sengaja dilumpuhkan agar tidak dapat berkembang hingga mampu melawannya.
Amangkurat I digambarkan sejarawan Merle C. Ricklefs dalam War, Culture, and Economy in Java 1677-1726 (1993) sebagai penguasa brutal tanpa sedikit pun keberhasilan atau kreativitas. “Jika Sultan Agung menaklukkan, menggertak, membujuk, dan bermanuver, Amangkurat I menuntut dan membantai” (hlm. 31). Dengan sedikit sekali perhatian kepada keseimbangan politik—sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa abad ke-17—Amangkurat I mencoba membangun kekuasaan terpusat dengan tujuan menyenangkan kepentingannya sendiri.
Akibat perilakunya itu, dia terasing dari semua aparatus pemerintahan dan elemen-elemen yang biasanya menjadi bagian konsensus: para pangeran, patih, tumenggung, dan pemuka agama. Amangkurat I juga dianggap tidak memiliki kualitas kebajikan yang harus dimiliki seorang raja. Dalam Serat Jaya Baya, kitab rahasia yang dianggap sakti karena bisa meramal masa depan, Amangkurat I dilukiskan dengan metafora negatif: Kalpa sru semune kenaka putung (masa kelaliman yang diibaratkan dengan kuku yang putus). “Masa lalim” maksudnya kekejaman pemerintahan raja, dan “kuku yang putus” maksudnya banyaknya panglima yang dibunuh tanpa guna.
Baca juga : 22 Oktober 1945, Hari Santri : Fatwa Resolusi Jihad Ulama untuk Kemerdekaan Indonesia
Baca juga : 27 Agustus 1628, Penyerbuan Ke Batavia: Serangan Agung Sultan Agung
Bersekutu dengan VOC
Berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat I sangat lunak terhadap Belanda. Ia bahkan memilih bersekutu dengan VOC daripada meminta dukungan rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintahannya, Amangkurat I melakukan perjanjian dengan VOC yang hakikatnya Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia.
Setiap tahunnya, VOC juga mengirimkan utusan ke Mataram, yang pada akhirnya ikut campur urusan politik kerajaan. Secara berangsur, wilayah kerajaan menyempit akibat aneksasi yang dilakukan Belanda sebagai imbalan atas intervensinya dalam pertentangan di kalangan keluarga kerajaan.
Oleh karena itu, tidak salah apabila menyebut masa pemerintahan Amangkurat I sebagai awal kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Ketidaksenangan rakyat dan para pejabat istana pun memuncak saat raja diketahui bermusuhan dengan putranya sendiri, Pangeran Adipati Anom.
Pemberontakan Trunojoyo Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat Mataram melakukan perlawanan terhadap Raja Amangkurat I di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura, yang juga mendapatkan dukungan dari para pejabat istana. Memasuki 1677, Keraton Plered berhasil direbut Pangeran Trunojoyo dan Amangkurat I terpaksa menyingkir ke arah Cirebon untuk meminta bantuan kepada VOC.
Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Trunojouo, yang sebelumnya bersekutu, justru terlibat konflik. Hal ini membuat Pangeran Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepadanya seperti kesepakatan sebelumnya. Akibatnya, Pangeran Adipati Anom memilih untuk beralih ke pihak ayahnya.
Akhir hidup Dalam pelariannya untuk meminta bantuan VOC, Amangkurat I jatuh sakit dan meninggal di Wanayasa (Banyumas) pada 10 Juli 1677. Jenazahnya kemudian dibawa ke Tegalwangi, kini masuk wilayah Kabupaten Tegal, untuk dimakamkan.
Setelah itu, Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk melumpuhkan Trunojoyo. Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada 1679, dan takhta Kesultanan Mataram diberikan kepada Adipati Anom dengan gelar Amangkurat II.
Kronologis Pembantaian
Setelah kematian Pangeran Alit, Amangkurat I memanggil empat orang pembesar keraton untuk menghadap. Ia merencanakan balas dendam tanpa menimbulkan kesan dialah otak di balik rencana itu. Keempat orang tersebut (Pangeran Aria, Tumenggung Nataairnawa, Tumenggung Suranata, dan Ngabehi Wirapatra) adalah orang-orang kepercayaan sang raja.
Bersama anak buah masing-masing, mereka menerima perintah untuk menyebar ke empat penjuru mata angin. Seperti diungkap sejarawan H.J. de Graaf dalam De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677 (1961), sang raja berpesan agar: “Jangan seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram luput dari pembunuhan” (hlm. 38).
Dan agar rencana berjalan lebih baik, mereka diminta menyelidiki lebih dahulu nama, keluarga, dan alamat para pemuka agama tersebut. Bagi Amangkurat I, ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Ketika permufakatan keji mulai dilakukan, Amangkurat sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton.
Semua sidang peradilan dan pisowanan yang melibatkan dirinya berpindah di dalam istana. Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berlangsung dengan lancar. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, ia memberi perintah-perintah terakhir kepada empat orang itu.
Ia meminta mereka agar bertindak sebaik-baiknya dan “membunuh semua laki-laki, wanita, dan anak-anak”. Aba-aba dimulainya pembantaian berupa bunyi letusan meriam Ki Sapujagat yang terpasang di halaman keraton.
Baca juga : Kisah pemuda Ashabul Kahfi, kekejaman penguasa dan perjuangan membela kebenaran
Baca juga : Salahudin Al Ayubi, Ulama Pembebas Yerusalem
Alun-Alun yang Berdarah
Saat semua persiapan sudah dilakukan, pasukan pembantai pun mulai berangkat ke kediaman para calon korban. Amangkurat I, penguasa yang digambarkan Soemarsaid Moertono dalam State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century (1968) sebagai “raja yang istimewa lalimnya”, mengamankan diri di dalam keraton dengan penuh ketakutan.
Bahkan di bawah penjagaan ketat para pengawal pribadinya yang paling kuat dan bisa dipercaya, ia masih merasa was-was dengan keputusannya sendiri. Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung.
Babad-babad Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Satu-satunya sumber yang bisa diandalkan hanyalah catatan Rijcklofs van Goen, pejabat VOC yang saat itu berdinas di Mataram, yang kemudian diterbitkan dalam De vijf gezantschapsreizen naar het hof van Mataram, 1648-1654 (1956).
Tapi yang pasti, pembantaian berlangsung amat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Hari itu, di suatu siang yang terik tahun 1648, sekitar 6000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram harus mati karena kekejian sang raja.
Mengutip keterangan van Goens dalam catatannya, H.J. de Graaf menggambarkan: “Belum setengah jam berlalu setelah terdengar bunyi tembakan, 5 sampai 6 ribu jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan.”
Seperti biasa, Amangkurat I selalu ingin tangannya bersih. Ia mengelakkan tanggung jawab atas tindakan kejinya itu. Esok hari setelah pembantaian berlangsung, ia tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut.
Selama satu jam di depan para pejabat, tidak satu patah kata pun terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam dan suasana kian mencekam. “Tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Sunan,” catat van Goens.
Dan di sinilah kedegilan Amangkurat I makin terlihat. Setelah mengucap beberapa kalimat yang menuduh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alit sehingga pantas mendapat balasan setimpal, ia memerintahkan delapan pembesar yang dicurigai untuk diseret ke hadapannya.
Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Sunan dengan mengangkat Alit menjadi raja. Dalam situasi macam itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengaku. Delapan pembesar itu akhirnya bernasib sama dengan para ulama: mereka beserta seluruh keluarganya dibunuh.
Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonnya dengan penuh amarah. Seperti dicatat van Goens, “Ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintahan ayahnya itu dalam suasana tercekam dan penuh kekhawatiran.”
*Disarikan dari berbagai sumber
Baca juga : Aidit, Mao Zedong dan Pidato di Sumur Tua
Baca juga : Dibalik Kecerian April Mop: Jejak Kekejaman Terhadap Umat Islam Andalusia